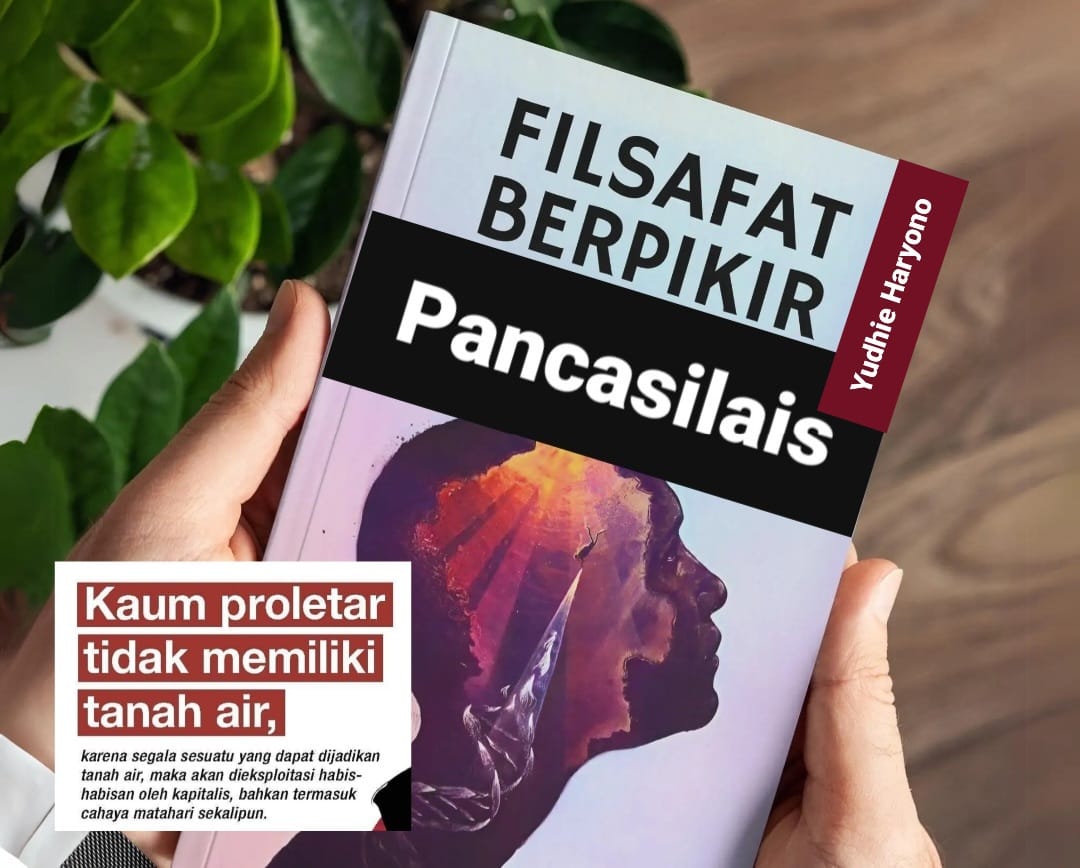Oleh: Prof. Dr. Yudhie Haryono (Rektor Universitas Nusantara) dan Agus Rizal (Ekonom Universitas MH Thamrin)
Balik arah. Kembali ke jatidiri. Apa salah satu jati diri kita? Ekonomi Pancasila. Sebab, ekonomi bukan sekadar sistem distribusi sumber daya dan cara menumpuk kekayaan serta hukum ketamakan. Sebaliknya, ia adalah cerminan dari nilai-nilai yang dipilih suatu bangsa-negara. Dalam konteks Indonesia, ekonomi yang sesuai dengan jiwa Pancasila bukanlah pilihan ideologis tambahan, melainkan bagian yang menyatu dengan amanat konstitusi: dus ia sangat konstitusional, rasional, riil.
Para pemikir besar Indonesia telah menekankan bahwa sistem ekonomi nasional harus bertumpu pada prinsip spiritual, kemanusiaan, keadilan, pemerataan dan kesejahteraan-kesentosaan kolektif, bukan semata pertumbuhan yang bersifat kuantitatif dan berorientasi personal, pasar dan nafsu berkuasa selamanya. Tanpa kesadaran ideologis, sejarah kita tercatat menjadi from the wealth of nations (tujuan negara) to the wealth of individual (karena berkhianatnya aparatus negara) to the wealth of squad/gang (karena kudeta konstitusi).
Di sini, gagasan ekonomi pancasila menolak sistem kapitalisme yang eksploitatif maupun sosialisme totaliter yang menekankan kepatuhan. Ia memastikan jalan tengah yang menghibridasi demokrasi ekonomi dengan partisipasi warga-negara melalui koperasi dan penguasaan strategis oleh negara (BUMN) untuk kepentingan umum. Di titik inilah lahir benih-benih dasar ekonomi Pancasila, yakni sistem ekonomi nasional yang menjunjung tinggi prinsip moralitas, solidaritas dan kedaulatan warga-negara atas ekonominya sendiri.
Pemikiran ekonomi yang berpijak pada nilai Pancasila memperingatkan sejak awal bahwa Indonesia tidak bisa dikelola hanya dengan teori-teori neoklasik yang dibentuk dalam konteks negara-negara industri Barat. Ekonomi Pancasila adalah sistem yang lahir dari realitas sosio-kultural bangsa Indonesia, bukan hasil tiruan dari model kapitalistik yang membungkus ketimpangan dengan dalih efisiensi. Sistem ini menekankan peran aktif negara dan warga-negara dalam menjamin keadilan distributif dan menolak liberalisasi ekonomi yang mengorbankan kepentingan mereka. Tanpa dimensi etika dan keberpihakan, pembangunan ekonomi akan berubah menjadi mesin akumulasi yang menciptakan ketimpangan antarwilayah dan antarwarga-negara.
Secara filosofis, hidup dan ekonomi kita tidak bisa sepenuhnya diajari oleh pikiran dan tindakan orang luar, karena semua didasari oleh fondasi jiwa-jiwa generasi leluhur (psychological genetic) dari generasi pendahulunya. Itulah pentingnya “sistem sendiri,” baik dalam berindividu, bermasyarakat dan bernegara. Itulah keniscayaan pancasila dan konstitusi asli yang keren karena merangkum jati diri dalam berekonomi dan dalam ipoleksosbudhankam.
Sayangnya, makin ke mari ide besar, jenius dan dahsyat ini lebih banyak dikenang sebagai romantisme sejarah ketimbang menjadi fondasi nyata dalam perencanaan pembangunan. Ia bahkan dicampakkan, dikhianati dan dihapuskan oleh banyak ekonom dan guru di sekolah-sekolah.
Akhirnya, dalam praktik kenegaraan arah pembangunan ekonomi Indonesia bergeser jauh dari amanat konstitusi yang secara tegas meletakkan keadilan sosial sebagai prinsip dasar sekaligus ultima kehidupan bernegara. Konstitusi Indonesia, khususnya dalam pembukaannya, menegaskan cita-cita untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nilai-nilai ini bukanlah hiasan retoris, melainkan landasan ideologis dan normatif yang bersifat mengikat.
Kenyataannya memang, kebijakan ekonomi nasional lebih banyak diarahkan oleh paradigma pasar yang kompetitif, individual dan liberal. Semua jelas bertentangan dengan semangat konstitusi tersebut. Ekonomi Indonesia tidak dapat dijalankan dengan asumsi-asumsi netral yang mengabaikan konteks sosiologis dan nilai-nilai dasar konstitusionalnya. Tanpa pijakan pada prinsip dasar negara, pembangunan kehilangan arah ideologis, dan ekonomi hanya menjadi instrumen pertumbuhan yang menguntungkan segelintir pihak. Dalam situasi seperti ini, konstitusi direduksi menjadi simbol legalistik tanpa kuasa korektif terhadap arah pembangunan yang menyimpang dari cita-cita awal berdirinya negara.
Harus disadari bahwa konstitusi Indonesia tidak hanya membentuk struktur negara, tetapi juga menetapkan arah ekonomi nasional yang berlandaskan keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Ketika kebijakan ekonomi dijalankan tanpa merujuk pada nilai-nilai tersebut, negara telah menyimpang dari kontrak sosial yang sah. Pertumbuhan ekonomi yang dilepaskan dari prinsip keadilan akan menghasilkan ketimpangan struktural yang bertentangan dengan cita-cita pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kerangka ini, ekonomi Pancasila bukan sekadar sistem alternatif, melainkan representasi konkret dari mandat konstitusi itu sendiri. Mengabaikannya sama dengan menanggalkan tanggung jawab konstitusional negara terhadap warganya. Keberpihakan terhadap keadilan sosial, dalam hal ini, bukan preferensi politik, melainkan keharusan hukum yang bersumber dari fondasi negara.
Sudah lama, kita disihir oleh narasi globalisasi dan kompetisi pasar bebas tanpa mengkritisi struktur ketimpangan yang menyertainya. Padahal, tidak ada satu pun sistem ekonomi yang netral. Memilih liberalisasi berarti memilih akumulasi pada segelintir aktor pasar. Memilih ekonomi Pancasila berarti kembali pada prinsip kedaulatan warga-negara atas ekonomi, sebagaimana telah dirumuskan dalam konstitusi dan diperkuat oleh narasi ideologis bangsa sejak kemerdekaan. Ini bukan tentang nostalgia, melainkan tentang menegaskan kembali arah pembangunan yang sah dan sahih secara historis, etis, dan yuridis.
Menghidupkan kembali ekonomi Pancasila berarti menyatukan arah pembangunan nasional dengan prinsip dasar negara. Ini bukan urusan teknis, melainkan keberanian politik dan kematangan intelektual. Dalam dunia yang semakin menyeragamkan model ekonomi, Indonesia memiliki keunikan untuk menawarkan alternatif—sebuah sistem ekonomi yang manusiawi, berdasar nilai, dan berakar kuat pada konstitusi. Di sini yang terlupakan bukan konsepnya, melainkan keberanian untuk menjalankannya. Ingatlah bahwa para guru bangsa telah menegaskan, “ketika sebuah bangsa depresi oleh belenggu ketakutan dan kecemasan, maka daya hidupnya dilumpuhkan oleh jeratan 4D: defeated (rasa pecundang), defective (rasa cacat), deserted (rasa diabaikan) dan deprived (rasa tercerabut) yang dihayati seolah-olah sebagai kenyataan sejati; yang riil; yang sesungguhnya.
Oleh sebab itu, hindari sikap takut dan cemas dalam bernegara (terutama pemimpinnya). Kini, mari optimis, berani dan bekerja jadi versi terbaik dari diri kita agar tidak khianat pada para pendiri republik dan Indonesia.