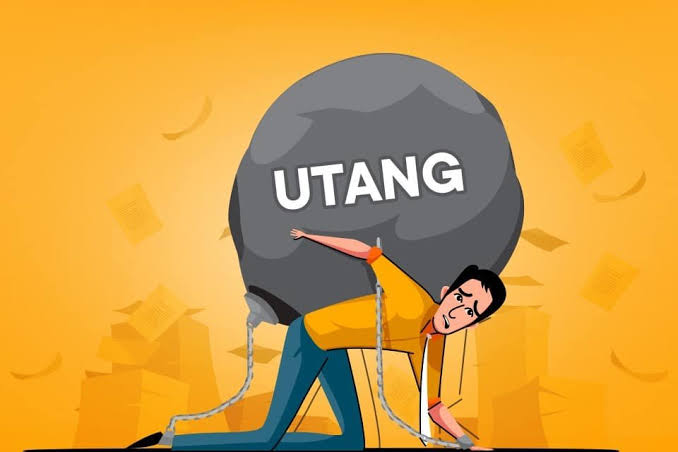Oleh: Yudhie Haryono (Rektor Universitas Nusantara) & Agus Rizal (Ekonom Universitas MH Thamrin)
Hutang kok ditradisikan? Dan, itu berulang dengan skema awal “defisit APBN.” Hampir setiap bulan, kita melihat dan mendengar pengumuman yang memilukan dari Kemenkeu, “kita mengalami defisit APBN, lalu solusinya berulang: hutang.” Tidak ada terobosan, tidak ada dentuman. Semua dibuat wajar dan tidak ada kejeniusan pengelolaan keuangan negara. Selama puluhan tahun kita hanya punya dua mantera: defisit dan hutang. Pasti itu jebakan. Pasti itu penjajahan via agensi lokal.
Sesungguhnya, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar selisih teknis antara pengeluaran dan penerimaan. Ia adalah indikator struktural yang mencerminkan kemampuan negara dalam mengelola sumber daya fiskal secara mandiri. Pada 2025, Kementerian Keuangan Republik Indonesia memproyeksikan defisit anggaran akan mencapai Rp662 triliun atau setara 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB)—lebih tinggi dari target awal pemerintah sebesar 2,53 persen. Proyeksi ini disampaikan melalui dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 yang diterbitkan pertengahan 2024 sebagai landasan penyusunan RUU APBN 2025. Kenaikan defisit ini bukan sekadar deviasi teknis, tetapi menjadi sinyal melemahnya kapasitas negara dalam menjaga kedaulatan fiskal secara berkelanjutan. Jadi, niat mendefisitkan APBN dan solusi hutang sudah ada dari pikiran, direncanakan dan dirilis tanpa desain antitesanya.
Dan, tren lima tahun terakhir menunjukkan pola defisit yang berulang-ulang walau fluktuatif. Pada tahun 2020, ketika pandemi COVID-19 memuncak, defisit APBN melonjak tajam hingga Rp956,3 triliun atau 6,14 persen dari PDB (Kemenkeu, 2021), menjadikannya yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia modern. Tahun-tahun berikutnya menunjukkan tren perbaikan: defisit turun menjadi Rp783,7 triliun pada 2021, lalu menyusut lagi menjadi Rp464,3 triliun pada 2022. Namun, pada 2024 defisit kembali naik menjadi Rp507,8 triliun, dan kini pada 2025 diproyeksikan meningkat lagi (Kemenkeu, 2024). Fakta ini menunjukkan bahwa upaya pemulihan fiskal pascapandemi masih belum stabil. Struktur pembiayaan negara tetap rapuh karena sangat bergantung pada penerbitan hutang dan instrumen keuangan jangka pendek.
Salah satu risiko terbesar yang menyertai pola pembiayaan ini adalah ketergantungan terhadap hutang luar negeri. Berdasarkan laporan Bank Indonesia kuartal IV 2024, total hutang luar negeri Indonesia telah mencapai US$398,2 miliar, dengan sekitar US$192,6 miliar berasal dari sektor pemerintah dan bank sentral. Sebagian besar hutang ini berdenominasi dolar AS dan yen, sehingga sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar. Dalam situasi depresiasi rupiah, beban pembayaran bunga dan pokok hutang melonjak drastis. Di sisi lain, hutang luar negeri yang diperoleh dari lembaga seperti Bank Dunia, IMF, atau pinjaman bilateral sering kali disertai persyaratan kebijakan tertentu. Ini mengurangi ruang gerak Indonesia dalam menetapkan kebijakan fiskal secara independen.
Secara teori fiskal klasik maupun kontemporer, defisit anggaran yang terus dibiayai melalui hutang publik akan mempersempit ruang kedaulatan negara dalam jangka panjang. Dalam pidato Nota Keuangan 2023, pemerintah mengakui bahwa dinamika global seperti kenaikan suku bunga The Fed dan gejolak geopolitik memberi tekanan besar terhadap portofolio hutang Indonesia. Ketika mayoritas pembiayaan negara bersumber dari pasar keuangan global, maka volatilitas eksternal dapat langsung mengganggu stabilitas fiskal domestik. Situasi ini bertentangan dengan prinsip ekonomi berdikari yang menempatkan negara sebagai aktor utama pembangunan, bukan sekadar perantara antara pemilik modal dan pelaksana proyek.
Masalah struktural lain yang tak kalah krusial adalah stagnasi rasio perpajakan. Data Kemenkeu 2023 mencatat rasio perpajakan Indonesia hanya berada di angka 10,3 persen dari PDB, jauh di bawah rata-rata negara berkembang yang berada pada kisaran 15,18 persen. Penerimaan negara belum mencerminkan potensi ekonomi riil, terutama karena belum optimalnya ekstensifikasi pajak dan resistensi politik terhadap reformasi sistem perpajakan super progresif. Di sisi lain, belanja negara masih berat di sisi rutin dan nonproduktif seperti subsidi energi ke konglomerasi dan belanja birokrasi. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2023 juga menyoroti bahwa efektivitas belanja negara dalam mendukung sektor produktif masih rendah, khususnya pada bidang pendidikan, riset, dan kedaulatan pangan.
Di sini, pemikiran ekonomi Pancasila harus menjadi dasar dalam membenahi persoalan fiskal dan anggaran negara. Dalam sistem ekonomi Pancasila, negara wajib hadir secara aktif menjamin keadilan sosial melalui distribusi pendapatan yang adil dan pembangunan yang merata. Instrumen anggaran tidak hanya dilihat sebagai alat teknokratis, tetapi sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap kesejahteraan warga negara. Asas kekeluargaan dan gotong royong menjadi prinsip utama. Karena itu, belanja negara harus diarahkan untuk mendukung sektor-sektor strategis nasional seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan industri berbasis sumber daya lokal. Dengan berpijak pada ekonomi Pancasila, setiap keputusan anggaran menjadi refleksi dari komitmen ideologis untuk membangun kedaulatan ekonomi yang berakar pada nilai-nilai luhur bangsa.
Untuk menjawab tantangan struktural ini, bangsa Indonesia tidak bisa terus bertahan dalam kerangka berpikir neoliberalisme yang menempatkan pasar sebagai pengatur utama pembangunan. Sudah saatnya Indonesia meninggalkan fondasi pemikiran ekonomi yang berakar pada mekanisme pasar bebas, privatisasi, liberalisasi dan deregulasi yang menafikan peran negara dan warganya dengan praktik keadilan sosial.
Sebagai gantinya, Indonesia harus kembali pada pemikiran ekonomi Pancasila dengan suatu sistem yang menempatkan negara dan koperasi sebagai pengelola sumber daya strategis, memastikan distribusi kekayaan secara adil, dan menekankan kolektivitas melalui gotong royong. Ekonomi Pancasila menolak dominasi modal asing atas kedaulatan kebijakan nasional dan menegaskan bahwa ekonomi harus dikendalikan oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran warga-negara.
Bangsa ini hanya akan mampu bertahan dan tumbuh menjadi peradaban besar jika kita berani meninggalkan cara berpikir dan bertindak yang dibentuk oleh logika neoliberalisme, dan berani menyambut sistem ekonomi politik berdasarkan Pancasila. Cara berpikir elitis, pro-pasar, pro-oligarki dan transaksional yang selama ini mendikte arah kebijakan fiskal harus dibongkar total. Kita tidak hanya butuh perubahan kebijakan, tetapi perubahan paradigma, keberpihakan dan penggantian agensi (ekonom). Dengan keberanian politik dan kesadaran ideologis, kita harus mengumandangkan: selamat tinggal neoliberalisme, selamat datang pasukan Pancasila dan pikiran-pikirannya.
Langkah awal yang harus dilakukan kita semua adalah mengganti seluruh ekonom hit-guys neolib sambil mengkonsolidasikan sistem penerimaan negara melalui optimalisasi pajak digital, pengurangan insentif fiskal yang tidak tepat sasaran, reformasi tata kelola perpajakan daerah, penetapan kurs tetap, perealisasian SWF (Sovereign Wealth Fund).
Di sisi belanja, perlu dilakukan audit menyeluruh atas proyek-proyek besar, termasuk dampaknya terhadap pemerataan ekonomi dan keterlibatan sektor koperasi dan usaha mikro. Lebih dari sekadar mengatasi defisit, reformasi ini harus diarahkan untuk membangun struktur fiskal yang adil, transparan, dan menjamin hak ekonomi-politik setiap warga-negara dalam jangka panjang secara konsisten.