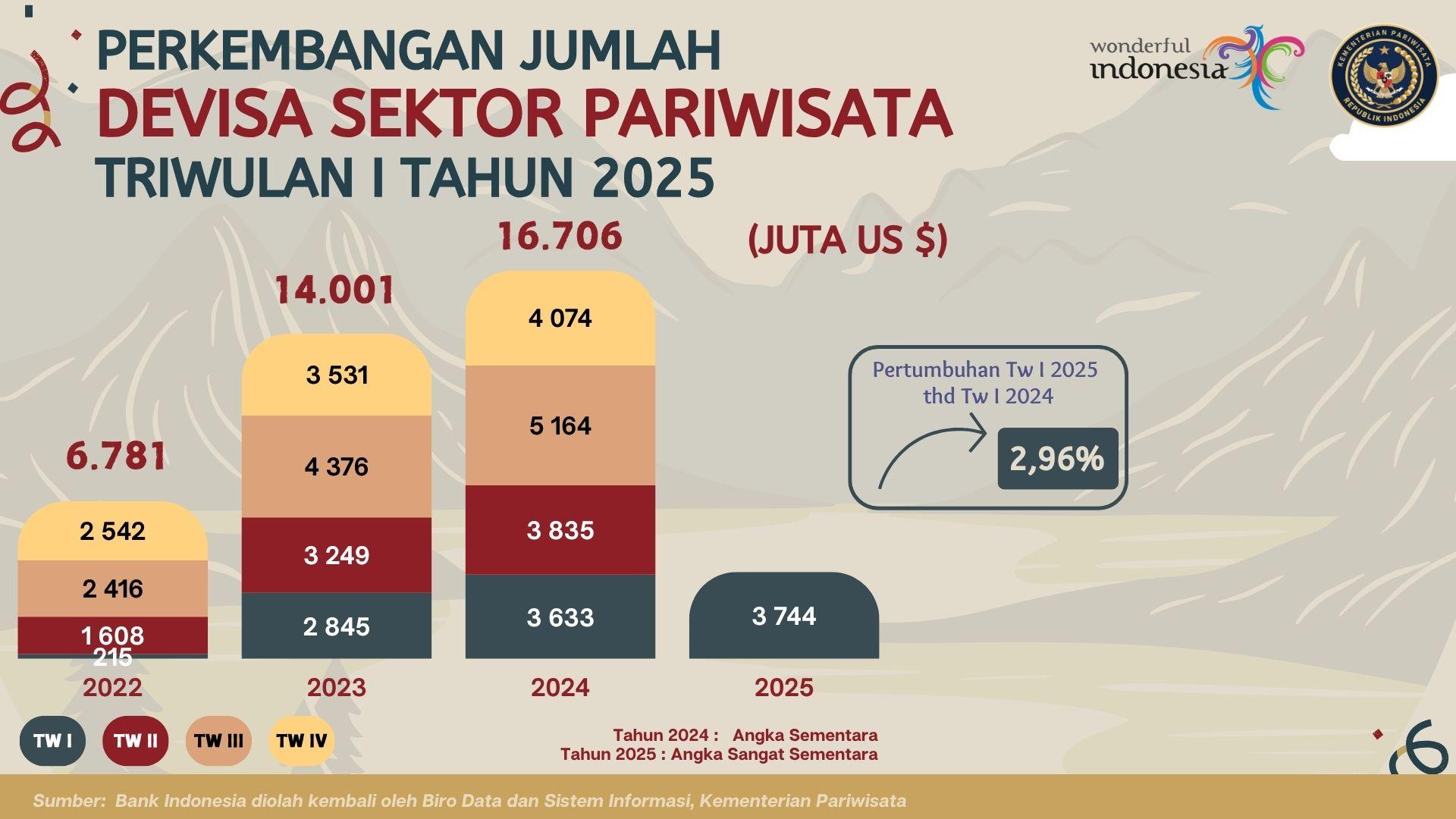Oleh: Yudhie Haryono (CEO Nusantara Centre) & Agus Rizal (Ekonom Universitas MH Thamrin)
Apa yang tidak hadir dalam kebijakan ekonomi lampau dan hari ini? Salah satunya adalah kebijakan devisa tanpa ideologi, tanpa muatan subtansi yang konstitutif, tanpa keinginan sebagai alat perang dagang. Dari pengalaman tersebut, kebijakan penggunaan devisa yang diatur dalam Undang-Undang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial (UUPNKS) akan membuka babak baru dalam tata kelola ekonomi Indonesia.
Hal yang absen dan disengaja dilupakan, akhirnya dihadirkan. Tak mudah karena negara berupaya merekonstruksi hubungan antara devisa, kedaulatan ekonomi, dan kesejahteraan-kesentosaan warga negara. Tentu, pendekatan ini tidak hanya bersifat teknokratis pro-pasar, tetapi juga ideologis—menempatkan devisa sebagai alat perjuangan serta pendaulatan ekonomi nasional, bukan sekadar instrumen transaksi global.
Ya. Selama beberapa dekade, pengelolaan devisa di Indonesia cenderung mengikuti paradigma liberal yang memposisikan arus valuta asing sebagai domain pasar. Negara berperan pasif, sementara stabilitas kurs dijaga dengan instrumen moneter semata. Mungkinkah itu bagian dari pengkhianatan para ekonom yang selama ini berkuasa? Waktu yang akan menjawabnya.
Akibatnya, sebagian besar cadangan devisa tersimpan di luar negeri dan kurang berdampak langsung terhadap sektor produktif domestik; tidak berdampak pada stabilitas ekonomi seluruh warga-negara. Melalui UUPNKS, negara ingin mengoreksi ketimpangan struktural ini dengan menegaskan hak dan kewenangan dalam menentukan arah penggunaan devisa secara strategis dan berkeadilan. Di sini bedanya, di sini subtansi ekonomi pancasila hadir dan memihak, ideologis dan waras.
Prinsip dasar yang diperkenalkan dalam kebijakan ini adalah bahwa devisa nasional merupakan bagian dari kekayaan negara yang penggunaannya harus diarahkan bagi kemakmuran umum. Negara tidak lagi sekadar mengawasi transaksi valas, tetapi mengarahkan alokasinya untuk kepentingan pembangunan jangka panjang. Kebijakan ini membuka ruang untuk menghubungkan cadangan devisa dengan pembiayaan proyek strategis, penguatan industri berbasis ekspor, serta pengendalian utang luar negeri agar tetap dalam batas rasional dan produktif.
Dimensi pengaturan selanjutnya menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan lembaga ekonomi nasional lain dalam menentukan prioritas penggunaan devisa. Pendekatan ini bersifat terstruktur, sistematis dan masif karena menempatkan devisa sebagai instrumen kebijakan ekonomi makro yang terintegrasi, bukan terpisah antar sektor. Dengan demikian, kebijakan devisa tidak hanya berorientasi menjaga nilai tukar, tetapi juga menstimulasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi riil serta distribusi kesejahteraan.
Kebijakan ini juga memberikan dasar bagi pemerintah untuk menata kembali hubungan antara devisa swasta dan devisa negara. Pemerintah berhak menetapkan sektor-sektor strategis yang wajib menempatkan sebagian devisanya di dalam negeri, baik melalui instrumen perbankan nasional maupun obligasi devisa negara. Tujuannya jelas: menjaga likuiditas nasional, memperkuat posisi neraca pembayaran, serta memastikan arus modal yang masuk dan keluar tetap dalam kendali negara tanpa menutup diri dari investasi asing yang produktif.
Paradigma baru ini menggeser orientasi lama yang memandang devisa hanya sebagai variabel moneter. Kini, devisa menjadi bagian dari politik ekonomi nasional yang berfungsi memperkuat kedaulatan, ketahanan dan kemartabatan ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan kecenderungan global di mana banyak negara menata ulang hubungan mereka dengan pasar valuta asing demi memperkuat basis ekonomi domestik yang lebih resilien terhadap tekanan eksternal.
Secara teoritis, arah kebijakan ini dapat dijelaskan melalui pendekatan developmental state dan teori economic sovereignty. Dalam kerangka developmental state, negara berperan aktif sebagai pemilik, pengelola, pelaksana dan pengarah sumber daya strategis, termasuk devisa, untuk mencapai tujuan industrialisasi dan kedaulatan-kemandirian ekonomi.
Sementara teori economic sovereignty menegaskan bahwa penguasaan negara terhadap arus modal dan devisa merupakan syarat utama agar kebijakan fiskal, moneter, dan industri tidak tunduk pada tekanan eksternal. Dengan kata lain, kendali atas devisa bukan semata soal ekonomi, tetapi tentang legitimasi politik dan kapasitas negara dalam menegakkan agenda pembangunan nasional.
Arah baru penggunaan daulat devisa dalam UUPNKS pada akhirnya bertujuan membangun ekonomi nasional yang tangguh, berdaulat, dan berkeadilan. Devisa tidak lagi dilihat sebagai angka dalam laporan cadangan internasional, tetapi sebagai energi strategis yang menopang daya tahan bangsa dalam menghadapi dinamika global.
Tanpa perubahan fundamental dalam pengelolaan devisa, ekonomi kita makin hari makin rapuh dan mudah takluk bahkan diterkam kekuatan ekonomi dunia, terutama oleh The Fed dan The ECB (European Central Bank). Dua lembaga otoritas keuangan yang sering menggunakan perang moneter dalam “memangsa ekonomi” negara lain.
Dengan pengelolaan yang rasional, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan warga negara, kebijakan ini menjadi fondasi penting menuju sistem ekonomi yang benar-benar berdiri di atas kaki sendiri. Menyitir tesis ekonom Joseph E. Stiglitz (2014), “devisa yang kuat akan menjadi penyangga dan pelindung ekonomi nasional dari guncangan luar dan predatori ekonomi global.” Sebuah nasihat yang jelas dan terang serta harus kita pastikan devisa kita adalah devisa penjaga kedaulatan dan peradaban. *